I.
PENDAHULUAN
a.
Latar Belakang
Salah
satu metode pemuliaan tanaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas
tanaman budidaya adalah poliploidisasi. Poliploidisasi merupakan penambahan
jumlah set kromosom pada suatu individu. Poliploidisasi diharapkan dapat
menjadi solusi untuk mendapatkan tanaman yang lebih unggul, mampu
mempertahankan sifat baik dari bentuk heterozigot, serta menghilangkan
sterilitas tanaman. Upaya peningkatan ploidi tanaman dapat dilakukan dengan mutasi
buatan menggunakan perlakuan mutagen berupa kolkisin.
Pada
tanaman, pertumbuhan dan perkembangan sel merupakan hal yang tidak terlepas
dari kemampuan sel untuk membelah. Pembelahan sel dapat diamati pada jaringan
yang aktif membelah. Pada tanaman, salah satu lokasi jaringan yang aktif
membelah adalah jaringan meristem yang terdapat pada ujung akar.
Setiap
spesies tanaman memiliki jumlah kromosom yang khas. Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) merupakan tanaman
budidaya yang memiliki jumlah kromosom 2n=16. Jumlah tersebut tergolong sedikit
sehingga diharapkan mudah untuk diamati. Tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) juga dapat dengan
mudah ditumbuhkan akarnya sehingga mudah untuk mendapatkan jaringan dengan sel
yang aktif membelah. Selain itu, bawang merah (Allium ascalonicum) juga dapat dengan mudah didapatkan. Oleh sebab
itu, pada praktikum ini akan dilakukan induksi poliploidisasi menggunakan
mutagen kolkisin pada tanaman bawang merah (Allium
ascalonicum) serta pengamatan terhadap fase-fase mitosis menggunakan
preparat akar tanaman bawang merah (Allium
ascalonicum).
b.
Permasalahan
1.
Bagaimanakah cara
induksi poliploidisasi terhadap tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) dengan menggunakan mutagen kolkisin?
2.
Bagaimana pengaruh
induksi poliploidi terhadap kromosom tanaman?
3.
Bagaimanakah fase-fase
mitosis yang teramati pada preparat akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum)?
c.
Tujuan
Tujuan dari pelaksanaan
praktikum ini adalah sebagai berikut.
1.
Melakukan induksi
poliploidisasi terhadap tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) dengan menggunakan mutagen kolkisin.
2.
Melihat dan mengamati
pengaruh induksi poliploidi terhadap kromosom tanaman.
3.
Mengenal fase-fase
mitosis dengan mengamati letak kromosom akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).
II.
TINJAUAN PUSTAKA
a.
Landasan Teori
Molekul
DNA pada inti sel makhluk hidup diketahui terdiri dari ratusan juta pasang basa.
Setiap makhluk hidup diketahui memiliki jumlah gen yang berbeda-beda. Pada saat
pembelahan, sel harus mampu membagi set materi genetik dengan sama kepada dua
sel anakannya. Untuk mendukung hal tersebut, sel memiliki cara tersendiri untuk
menyederhanakan struktur gennya. DNA dalam sel akan berikatan dengan kompleks
protein dan membentuk nukleosom. Setiap nukleosom memiliki sekitar 8 protein
histon yang mengemas DNA. Histon memiliki muatan positif sedangkan DNA memiliki
muatan negatif. Kompleks antara keduanya akan menimbulkan keseimbangan.
Gambar
1. Kromosom merupakan benang kromatin yang terkondensasi (BSCS, 2006)
Nukleosom-nukleosom
dalam inti sel kemudian akan membentuk benang-benang yang disebut kromatin.
Benang kromatin inilah yang kemudian akan memadat dan membentuk struktur
kromosom (Gambar 1). Masing-masing spesies makhluk hidup memiliki jumlah
kromosom yang berbeda-beda.
Gen-gen
dalam Mendelian diketahui memiliki lokus yang spesifik di dalam kromosom
(Campbell et al, 2008). Gen-gen dalam
kromosom tersebut dapat mengalami segregasi dan pemilahan bebas sesuai dengan
prinsip Mendelian. Perilaku kromosom tersebut mempengaruhi pewarisan sifat dari
indukan kepada anakan serta mempengaruhi fenotip yang nantinya akan terlihat
pada anakan.
Kromosom
terdiri dari beberapa bagian diantaranya lengan kromosom, sentomer, telomer,
serta kinetokor. Sentromer merupakan bagian pengikat gelendong saat pembelahan
sel (Syukur et al, 2015). Sentromer
menentukan bentuk kromosom. Pada sentromer terdapat kinetokor yang berfungsi
sebagai tempat pelekatan benang spindel.
Gambar
2. Struktur Kromosom (Pierce, 2012)
Terdapat
beberapa macam kromosom pada sel eukariotik. Macam-macam kromosom tersebut di didasarkan
pada rasio lengan atau indeks sentromer yang dimiliki oleh kromosom tersebut
(Tabel 1).
Tabel
1. Klasifikasi kromosom berdasarkan rasio lengan atau indeks sentromer (Syukur,
2015)
|
Indeks
Sentromer |
Rasio
Lengan |
Posisi
Sentromer |
Klasifikas |
|
50,0 |
1,0
≤ RL ≤ 1,7 |
Median |
Metasentrik |
|
37,5-49,9 |
1,7
≤ RL ≤ 3,0 |
Submedian |
Submetasentrik |
|
25,0-37,4 |
3,0
≤ RL ≤ 7,0 |
Subterminal |
Subtelosentrik |
|
0,1-24,9 |
7,0
≤ RL ≤ ∞ |
Daerah
terminal |
Akrosentrik |
|
0 |
∞ |
Terminal |
Telosentrik |
Sebagian
besar organisme eukariotik merupakan diploid (2n) (Pierce, 2012). Meskipun
demikian, terkadang terdapat kegagalan dalam mitosis maupun meiosis sehingga
mengakibatkan adanya set kromosom ganda dalam sel. Hal ini mengakibatkan sel
tersebut mengalami poliploidisasi.
Poliploidi
merupakan peristiwa yang umum terjadi pada tanaman namun cukup jarang pada
hewan. Pada tanaman, adanya poliploidi seringkalan dimanfaatkan untuk
kepentingan agrikultur seperti dalam peningkatan kualitas gandum, kentang, dan
lain sebagainya. Terdapat dua macam poliploidi yaitu autopoliploidi serta
allopoliploidi.
Autopoliploid
dapat terjadi apabila terdapat penambahan jumlah set kromosom akibat kegagalan
mitosis atau meiosis. Misal, saat sel gagal mengalami mitosis, suatu sel bisa
jadi memiliki 4 set kromosom (4n). Peristiwa ini disebut dengan autotetraploid.
Organisme 4n nantinya akan membentuk gamet 2n. Allopoliploid terjadi karena
adanya hibridisasi antara dua spesies sehingga masing-masing sel induk
menyumbangkan set kromosomnya pada anakan. Individu yang dihasilkan dari
peristiwa allopoliploidi biasanya tidak mampu berkembangbiak secara seksual. Poliploidi
akan meningkatkan ukuran genom sehingga poliploidi seringkali dikaitkan dengan
adanya peningkatan ukuran sel. Pemulia biasanya memanfaatkan hal ini untuk
meningkatkan kualitas tanaman.
Kolkisin merupakan alkaloid mutagen
dengan rumus kimia C22H25O6N yang berasal dari
umbi tanaman Cochichum autumnale
(Suminah et al, 2002). Kolkisin pada
konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan poliploidi pada tanaman. Umumnya
konsentrasi kolkisin yang digunakan memiliki rentahg 0,01% hingga 1%. Kolkisin
dapat berpengaruh pada mikrotubul. Mikrotubul memiliki peran yang penting dalam
siklus sel dan mitosis. Kolkisin adalah agen depolimerisasi mikrotubul yang
telah lama digunakan untuk menginduksi pemberhentian siklus sel sehingga
terjadi poliploidisasi (Caperta et al,
2006).
Salah satu metode yang sering digunakan
dalam pengamatan kromosom sel adalah metode squash.
Metode ini memiliki beberapa tahapan yaitu tahap fiksasi, tahap maserasi, tahap
pewarnaan, serta tahap pemencetan. Pada tahap fiksas digunakan asam asetat
glasial yang bertujuan untuk mempertahankan kesegaran material tanaman. Adanya
tahapan fiksasi bertujuan untuk mempertahankan komponen dari sel-sel tanaman
sehingga sebagaimana dalam keadaan hidup. Dalam tahap maserasi, HCL 1N
digunakan dengan tujuan untuk melisiskan lamela tengah. Pada tahap pewarnaan,
aseto orsein digunakan dengan tujuan untuk mewarnai kromosom (Muhlisyah et al, 2014).
Pembelahan sel secara
mitosis
Pembelahan
sel merupakan serangkaian peristiwa penting untuk memproduksi dua sel yang sama
dari satu sel induk. Pada eukariotik, pembelahan sel somatik meliputi beragam
fase yang memerlukan replikasi akurat serta pembagian yang seimbang dari
informasi genetik yang dikodekan oleh DNA sel. Setiap sel anakan harus mewarisi
satu set kromosom yang identik (BSCS, 2006). Pembelahan sel sangat diperlukan
untuk pertumbuhan maupun penggantian sel-sel lain yang rusak.
Sel
memiliki siklus untuk dapat membelah. Siklus sel terdiri dari fase yaitu mitosis dan interfase (Gambar 3). Mitosis
merupakan proses pemisahan dan pendistribusian kromosom dalam pembelahan
sedangkan interfase adalah jeda diantara pembelahan sel. Dalam interfase, sel tidak semata-mata
beristirahat. Pada interfase, terdapat fase-fase lain yaitu G1, S dan G2.
Masing masing fase dalam interfase tersebut memiliki peran penting dalam
mempersiapkan mitosis.
Gambar 3. Siklus sel (BSCS, 2006)
Interfase
meliputi 90% waktu yang diperlukan dalam siklus sel (Campbell et al, 2008). Pada fase G1, sel terus
tumbuh dengan menghasilkan protein dan organel sitoplasma seperti mitokondria
dan retikulum endoplasma. Pada fase S, sel melakuan duplikasi kromosom. Sedangkan pada fase G2, sel terus bertumbuh
dan menyelesakan persiapan untuk fase mitotis.
Sel
bersifat autonom sehingga sel mampu mengatur bagaimana pembelahan yang akan
dilakukan olehnya dengan adanya koordinasi dengan lingkungan. Kontrol
pembelahan sel secara umum digambarkan sebagai berikut (Gambar 4).
Gambar
4 . Siklus sel (Lodish et al, 2003)
Dalam
pembelahan sel, siklin merupakan sub unit regulator berupa protein kinase
heterodimer yang meningkat dan menurun seiring dengan terjadinya siklus sel.
CDK (Cyclin-Dependent-Kinase) tidak dapat bekerja tanpa adanya asosiasi dengan
siklin. Setiapkali CDK dapat berasosiasi dengan siklin maka akan ada protein
tertentu yang terfosforilasi dengan adanya kompleks siklin-CDK. Pada saat sel
tersimulasi untuk bereplikasi, siklin-CDK pada G1 teraktifasi. Kompleks ini
mempersiapkan sel untuk memasuki fase S. Persiapan tersebut berupa aktifasi
faktor transkripsi yang akan meningkatkan transkripsi sejumlah gen yang
diperlukan untuk sintesis DNA serta gen yang akan mengkode siklin-CDK paa fase
S. Pada akhir G1, kompleks siklin –CDK menginduksi degredasi dari inhibitor
fase S dengan memfosorilasi dan menstrimulasi poliubiquitinasi dengan multi
protein SCF ubiquitin ligase. Dengan adanya poliubiquitinasi, proteasom
kemudian akan mengaktifasi siklin-CDK fase S. Setelah aktif, kompleks tersebut
kemudian akan mengaktifasi protein yang membentuk kompleks prereplikasi DNA.
Kompleks
siklin-CDK pada fase S dan G2 terbentuk untuk memastikan sintesis DNA selesai.
Dengan adanya defosforilasi pada inhibitor, siklin-CDK mitotsis akan
menstimulasi kondensasi kromosom, penghilangan membran ini, pembentukan
spindel, serta penyusunan kromoson pada lempeng metafase. Siklus sel terus
berlanjut dengan adanya APC hingga pembelahan sel terjadi karena mitosis
tersebut.
Mitosis
merupakan suatu bagian dari siklus sel. Di
dalam mitosis, terdapat fase-fase sebagai berikut (Tabel 2) (Campbell et al, 2008).
Tabel 2. Fase-fase
dalam mitosis
|
Fase
Mitosis |
Keterangan |
|
Profase
|
Serat
kromatin terkondensasi menjadi kromosom diskret yang teramati dengan
mikroskop cahaya, nukleolus lenyap, setiap kromosom terduplikasi tampak
sebagai sister kromatid yang tersambung pada sentromernya dan sepanjang lengannya
dengan adanya kohesin, gelendong mitotik mulai terbentuk, terdapat
kutub-kutub. |
|
Prometafase |
Selaput
nnukleus terfragmentasi, mikrotubulus menjulur dan memasuki wilayah nukleus,
kromosom semakin terkondensasi. Masing-masing kromatid memiliki kinetokor.
Beberapa mikrotubulus melekat pada kinetokor dan menarik-narik kromosom. |
|
Metafase |
Kromosom
berjejer di bidang pembelahan. |
|
Anafase
|
Protein
kohesin terbelah, masing masing sister kromatid memisah. Kromosom bergerak ke
arah kutub masing-masing. sel memanjang saat mikrotubulus non kinetokir
memanjang. Kedua kutub sel akan memiliki set kromosom yang sama pada akhir
anafase |
|
Telofase
|
Dua
nukleus anakan terbentuk dalams el. Selaput nukleus muncul dari fragmen
selaput nukleus sel induk dan bagian-bagian lain dari sistem endomembran.
Nukleolus muncul kembali, kromsom menjadi kurang terkondensasi. Pembagian
materi genetik (mitosis) telah selesai. |
|
Sitokinesis |
Pembelahan
sitoplasma terjadi. Terjadi pembentukan lempeng sel. |
Sumber gambar: http://wiki.district87.org/index.php/Cell_division,
http://everestmap.com/wp-content/uploads/2013/07/Meiosis-In-Plants.jpg
b.
Hipotesis
Berdasarkan uraian pada
landasan teori, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut.
1.
Mutagen kolkisin dapat
menginduksi poliploidisasi pada tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).
2.
Induksi poliploidi
dapat mengakibatkan peningkatan jumlah set kromosom serta ukuran sel tanaman
bawang merah (Allium ascalonicum).
3.
Fase-fase mitosis dapat
diamati pada ppreparat akar bawang merah (Allium
ascalonicum) berdasarkan posisi kromosomnya.
III.
METODOLOGI PENELITIAN
a.
Alat
Alat
yang digunakan dalam praktikum ini adalah petri disk, pisau, pipet tetes, gelas
benda, dan penutup, mikroskop, optilab, serta kuas.
b.
Bahan
Bahan
yang digunakan dalam praktikum ini adalah bawang merah (Allium ascalonicum, 2n=16), larutan kolkisin konsentrasei 0,05% dan
0,03%, akuades, asam asetat glasial, HCl, gliserin, serta Acetoorcein.
Alat dan bahan yang digunakan dapat
dilihat pada Lampiran 1.
c.
Cara kerja
Dalam
praktikum ini, bawang merah dikecambahkan terlebih dahulu. Keesokan harinya,
setelah bawang merah keluar akar dilakukan perlakuan kolkisin 0,05% selama 24
jam pada suhu kamar untuk kelompok perlakuan sementara perlakuan kontrol tetap
diteruskan perkecambahannya. Keesokan harinya, masing-masing bawang merah baik
kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol dicuci bersih dan bagian ujungnya
dipotong 2-3 mm. Potongan akar bawang merah kemudian dimasukkan ke dalam
kolkisin 0,03% selama 24 jam pada suhu 4oC untuk prafiksasi.
Setelah
dilakukan prafiksasi, potongan akar bawang kemudian dipindahkan ke dalam flakon
berisi AAG selama 10 menit pada suhu 4oC untuk difiksasi. Setelah 10
menit fiksasi, akar bawang selanjutnya dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali
serta dimaserasi dengan HCl 1N selama 5 menit pada suhu 55oC.
Selanjutnya, akar bawang kembali dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali. Akar
bawang kemudian diwarnai dengan perendaman selama 30 menit dalam asetoorsein.
Akar bawang selanjutnya diambil dan ditempatkan pada gelas preparat dan
ditetesi gliserin untuk disquash lalu diamati dibawah mikroskop.
IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada praktikum ini telah dilakukan
induksi poliploidisasi terhadap tanaman bawang merah (Allium ascalonicum) menggunakan mutagen kolkisin, serta pengamatan
fase-fase mitosis pada preparat akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).
Dalam induksi poliploidisasi, bawang
merah ditumbuhkan akarnya kemudian dijadikan dua kelompok yaitu kelompok
kontrol serta kelompok perlakuan. Pada kelompok perlakuan, tanaman direndam
dengan kolkisin 0,05% selama 24 jam, sedangkan tanaman kontrol direndam dengan
akuades. Perendaman kelompok perlakuan dengan kolkisin 0,05% bertujuan untuk
menginduksi terjadinya poliploidisasi pada tanaman bawang merah. Setelah itu,
baik kelompok perlakuan maupun kontrol kemudian dicuci dan dipotong ujung
akarnya sekitar 2-3 mm.
Potongan akar bawang dari tanaman
kontrol maupun perlakuan selanjutnya direndam dalam flakon berisi kolkisin
0,03% untuk prafiksasi selama 24 jam pada suhu 4oC. Tahapan
prafiksasi bertujuan untuk menghilangkan sisa deposit pada dinding sel,
terutama deposit lilin maupun minyak. Selain itu, tahapan ini juga berperan
dalam kondensasi kromosom. Setelah tahapan prafiksasi, potongan akar bawang
merah kemudian dipindahkan dalam flakon berisi asam asetat glasial (AAG) selama
10 menit pada suhu 4oC untuk fiksasi. Perlakuan ini bertujuan untuk
mempertahankan kondisi sel sebagaimana ketika sel tersebut hidup. selanjutnya
dilakukan pencucian dengan akar bawang sebanyak 3 kali. Pencucian bertujuan
menghentikan proses-proses yang masih berlangsung karena zat-zat yang
digunakan.
Potongan akar bawang merah selanjutnya
dimaserasi menggunakan HCl 1N selama 5 menit pada suhu 55oC.
Perlakuan ini bertujuan untuk melisiskan lamela tengah sehingga antar sel
tanaman satu sama lain akan dapat terpisah. Selain itu, perlakuan ini juga
mengakibatkan sel menjadi lebih lunak karena adanya pelunakan dinding sel
dengan pemutusan rantai polisakarida. Setelah maserasi, potongan akar bawang
merah kembali dicuci dengan akuades sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilakukan
pewarnaan menggunakan perendaman asetoorsein selama 30 menit. Pewarna
asetoorsein akan mewarnai kromosom sehingga dapat mudah teramati di bawah
mikroskop. Setelah itu, potongan akar diambil dan diletakkan di atas gelas
preparat serta diberi gliserin. Potongan akar yang telah diberi gliserin
kemudian ditutup dengan gelas penutup dan dilakukan pemencetan untuk memisahkan
sel-sel pada jaringan akar sehingga dapat teramati memisah dengan mikroskop.
Hasil pengamatan poliploidisasi bawang
merah yang tramati pada akarnya adalah sebagai berikut.
Tabel
3. Hasil Pengamatan Jaringan akar bawang pada kelompok kontrol dan pengamatan
|
Kelompok
|
Gambar |
|
Kontrol |
|
|
Perlakuan
|
|
Pada hasil pengamatan di atas, terlihat
bahwa dengan perbesaran yang sama sel-sel hasil perlakuan memiliki ukuran sel
yang jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran sel pada kelompok kontrol.
Selain itu, pada kelompok perlakuan terlihat bahwa terdapat beberapa sel yang
memiliki inti sel ganda (lingkaran pada gambar). Pada kelompok perlakuan,
dengan adanya perlakuan menggunakan kolkisin 0,05% maka terjadi perusakan
miktobutulus. Mikrotubulus tersusun dengan adanya polimerisasi tubulin alfa dan
tubulin beta. Keberadaan kolkisin menghambat polimerisasi tubulin alfa dan
tubulin beta yang menyusun mikrotubulus.
Selain mengubah sel secara mikroskopis,
melalui pengamatan langsung juga ditemui adanya perbedaan yang cukup berarti
pada morfologi akar bawang merah. Pada kelompok kontrol, akar bawang merah
cenderung memanjang dan kecil. Sedangkan pada kelompok perlakuan, akar
cenderung lebih besar dan pendek.
Gambar 4. Perbedaan morfologi akar pada
kelompok kontrol dan perlakuan (kiri:
kontrol: akar kecil dan panjang, kanan: perlakuan, akar besar dan pendek)
Pada gambar di atas terlihat jelas
adanya perbedaan morfologi yang ditimbulkan oleh adanya perlakuan kolkisin.
Pada akar bawang merah dengan perlakuan kolkisin, mikrotubulus tidak dapat
terbentuk sehingga proses pemanjangan sel maupu pembelahan sel terganggu.
Akibatnya morfologi akar menjadi pendek dan besar. Sedangkan pada kelompok
kontrol sel akar dapat membelah dan tumbuh dengan normal karena tidak ada
kendala pada pembentukan mikrotubul sehingga menunjukkan morfologi akar yang
normal. Berdasarkan hasil perhitungan kromosom, diketahui bahwa pada sel
kontrol terdapat 16 kromosom yang terhitung (Gambar 6). hal ini sesuai bahwa 2n pada bawang merah
memiliki 16 molekul kromosom. Namun demikian, pada kelompok perlakuan jumlah
kromosom sulit diidentifikasi karena kromosom saling berhimpitan satu sama lain
dan terlihat sangat padat (Gambar 6).
Selain mengamati ukuran sel serta keadaan
kromosomnya, pada praktikum ini juga diamati adanya fase-fase mitosis yang
tampak pada sel dengan adanya posisi tertentu dari kromosom-kromosom dalam sel.
Pada praktikum ini fase-fase yang teramati dapat dilihat pada tabel 4 berikut.
Tabel
4. Hasil Pengamtan fase-fase mitosis
|
Fase
Mitosis |
Gambar |
Keterangan |
|
Profase |
|
Kondensasi
kromosom terjadi, membran inti mulai menghilang |
|
Prometafase |
|
Kromosom
mengalami kondensasi lebih lanjut serta mulai terikat pada benang spindel |
|
Metafase
|
|
Kromosom
terikat pada benang spindel dan dijajarkan di tengah |
|
Anafase
|
|
Kromosom
masing-masing mulai ditarik ke arah kutub sel. |
|
Telofase |
|
Terdapat
dua inti sel serta mulai terjadi pembentukan membran inti kembali. |
|
Sitokinesis |
|
Terbentuk
lamela tengah yang memisahkan kedua sel anakan baru. |
Pada pengamatan fase-fase mitosis sel,
diketahui terdapat fase dari profase hingga sitokinesis yang teramati.
Keberadaan sel-sel yang teramati mengalami pembelahan dikarenakan jaringan yang
diamati adalah jaringan meristem ujung akar. Jaringan meristem merupakan
jaringan yang bersifat embrionik sehingga aktif membelah. Sel-sel yang masih
muda seperti yang teramati pada preparat yang digunakan memiliki inti sel yang
terlihat besar. Hal ini dikarenakan sel belum banyak mengalami pertumbuhan
lanjut sehingga bagian lain selain inti sel belum banyak terbentuk.
V.
KESIMPULAN
1.
Induksi poliploidisasi
tanaman bawang merah (Allium ascalonicum)
dapat dilakukan dengan menggunakan mutagen kolkisin.
2.
Induksi poliploidi
menggunakan mutagen kolkisin meningkatkan jumlah set kromosom pada tanaman
bawang merah (Allium ascalonicum).
3.
Terdapat fase profase,
prometafase, metafase, anafase, serta telofase pada fase-fase mitosis yang
teramati dengan melihat letak kromosom akar tanaman bawang merah (Allium ascalonicum).
VI.
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. Cell Division. Online http://wiki.district87.org/index.php/Cell_division
diakses Sabtu, 20 Mei 2017
Anonim. Meiosis in Plant. Online. http://everestmap.com/wp-content/uploads/2013/07/Meiosis-In-Plants.jpg
diakses Sabtu, 20 Mei 2017
BSCS. 2006. Biology: A Molecular Approach,
9th edition. BSCS
Caperta, A., Delgado, M., Ressurreição, F. et al. 2006. Colchicine- induced polyploidization depends on tubulin polymerization in c-metaphase
cells. Protoplasma 227: 147. doi:10.1007/s00709-005-0137-z
Lodish, Harvey F. 2003. Molecular Cell Biology.
Publisher, W. H. Freeman
Muhlisyah,
Nurul, Cut Muthiadin, Baiq Farhatul Wahidah, Isna Rasdianah Aziz. 2012.
Preparasi Kromosom Fase Mitosis Markisa Ungu (Passiflora edulis) Varietas
Edulis Sulawesi Selatan. Biogenesis:
Vol 2, No. 1, Juni 2014, hal 48-55
Pierce,
B. A. 2012. Genetics:
A conceptual approach. New York: W.H. Freeman.
Suminah, Sutarno, Ahmad Dwi Setyawan. 2002. Induksi
Poliploidi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.) dengan Pemberian Kolkisin. Biodiversitas Vol 3 No. 1















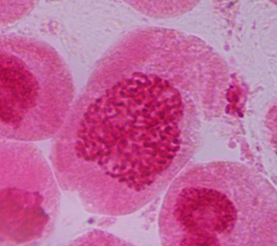

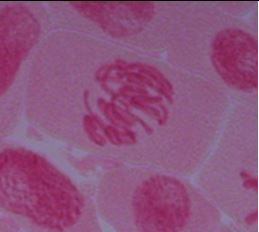







No comments:
Post a Comment